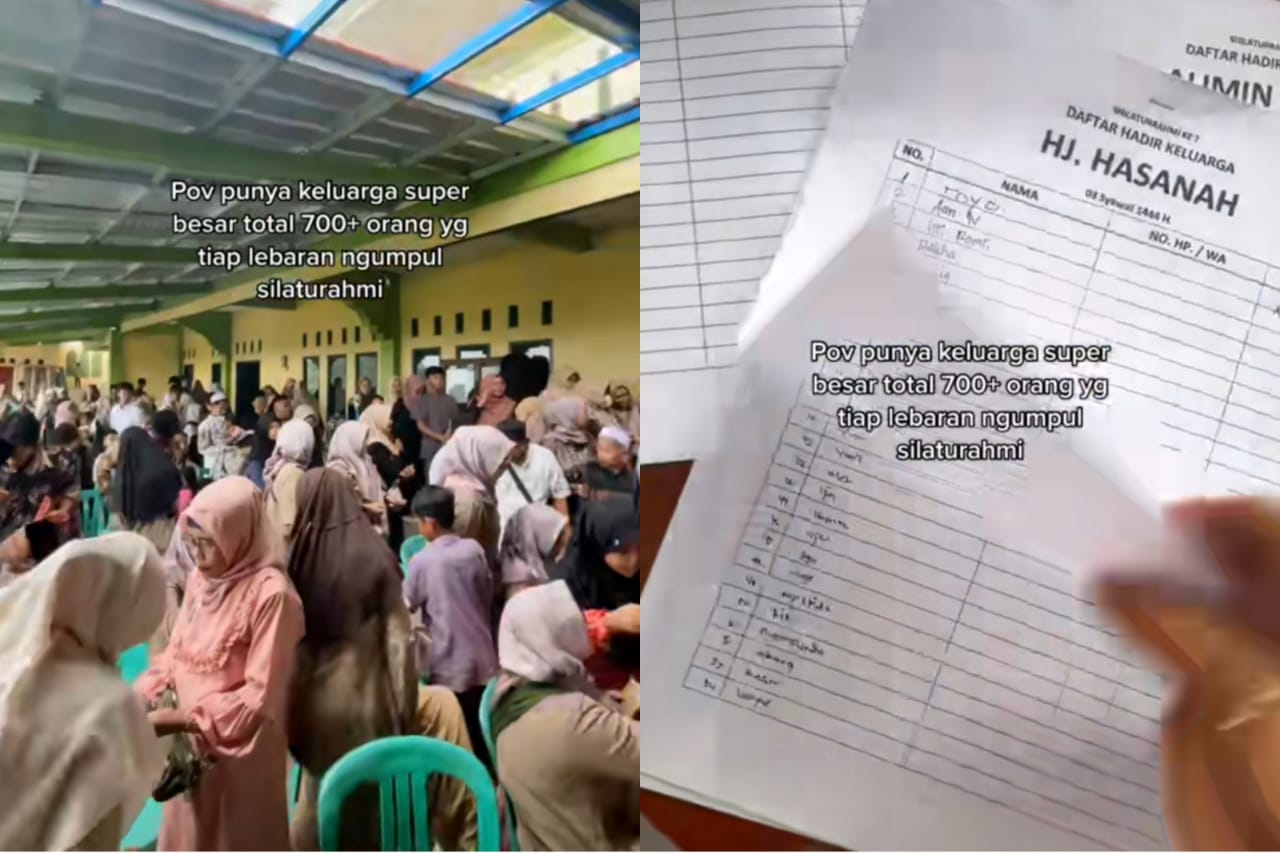Kembali dalam Kabut, Pulang dalam Kekosongan
Gerimis tipis membasahi aspal di depan rumah tua itu. Sebuah siluet kurus, terhuyung-huyung, muncul dari balik remang senja. Langkahnya gontai, seolah setiap pijakan adalah beban tak tertahankan. Ini Amara. Atau setidaknya, seseorang yang sangat mirip dengannya.
Lima tahun lalu, Amara menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran tak membuahkan hasil. Kini, ia kembali, muncul begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa ingatan. Hanya tatapan mata yang kosong dan kebingungan mendalam.
Ibunya, Lena, adalah yang pertama melihatnya. Tangis haru bercampur histeria meledak. Ayahnya, Arya, mendekap Amara erat, namun ada kengerian samar dalam pelukan itu. Amara yang kembali ini, terasa sangat berbeda.
Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat pasi. Ada bekas luka samar di pergelangan tangannya, tak pernah ada sebelumnya. Matanya, dulu penuh tawa, kini memancarkan kehampaan yang menakutkan. Ia menatap orang tuanya seolah mereka orang asing.
"Amara, ini Ibu," Lena berbisik, suaranya pecah.
Amara hanya mengerjap. Bibirnya bergerak, namun tak ada suara keluar. Ia seperti boneka yang baru dihidupkan, masih belajar bernapas.
Rumah itu, yang seharusnya menjadi pelabuhan aman, terasa asing baginya. Setiap sudut, setiap perabot, memancarkan aura yang salah. Foto-foto keluarga di dinding, dengan wajahnya yang dulu ceria, terasa seperti lelucon kejam.
"Ini kamarmu, sayang," Arya menuntunnya. Kamar tidur itu seharusnya familiar. Ranjang dengan selimut favoritnya, meja belajar penuh buku, poster band kesukaannya. Tapi Amara hanya memandangnya dengan kerutan di dahi.
Ada sesuatu yang aneh. Sebuah lukisan abstrak baru tergantung di dinding kamarnya. Dulu, tempat itu ditempati peta dunia besar yang penuh pin penanda tempat impiannya. Lukisan itu terasa dingin, warnanya mengganggu.
Makanan yang disajikan Lena, masakan kesukaan Amara, tak disentuh. Amara hanya menatapnya kosong, seolah tak mengenali aroma atau rasa. Ia hanya minum air, dan itupun dengan gerakan kaku.
Malam pertama adalah neraka. Amara tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, bergumam kata-kata tak jelas. Terkadang, ia menjerit pelan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyiksanya.
"Mereka," bisiknya suatu kali, suaranya parau. "Mereka melihatku."
Lena dan Arya saling pandang. Siapa "mereka"? Amara tidak bisa menjawab, hanya gemetar.
Dokter Friska, psikiater terkemuka, dipanggil. Ia mendiagnosis amnesia disosiatif parah. Trauma berat, katanya, menyebabkan otaknya memblokir kenangan. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar amnesia.
Amara seringkali berbicara dengan bahasa aneh. Bukan bahasa yang dikenal di bumi. Sebuah rangkaian nada dan desisan, terdengar seperti bisikan angin di lorong kosong. Itu membuat bulu kuduk berdiri.
Kadang ia akan menunjuk ke sudut ruangan yang kosong, matanya membesar ketakutan. "Ada di sana," katanya. "Menunggu."
Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan dari lampu tidur.
Beberapa hari berlalu. Amara mulai berjalan-jalan di rumah. Ia menyentuh benda-benda, seolah menguji keberadaan mereka. Sebuah vas bunga yang dulu selalu ada di meja ruang tamu, kini diganti dengan patung logam yang aneh.
"Ini bukan vas Ibu," Amara bergumam pada dirinya sendiri.
Lena mendekat. "Vas yang mana, sayang? Itu selalu ada di sana."
Amara menatap Lena dengan tatapan aneh. Sebuah kilatan ketakutan melintas di matanya. Seolah Lena berbohong, atau ia sendiri yang gila.
Amara tak bisa mengingat teman-temannya. Ia tak mengenali foto masa kecilnya bersama sahabat karibnya, Dian. Bahkan ketika Dian datang berkunjung, Amara hanya menatapnya dengan tatapan hampa.
"Siapa ini?" tanyanya, membuat Dian menangis.
Rasa bersalah dan kebingungan melanda Amara. Ia tahu ia seharusnya tahu. Otaknya berteriak nama-nama, kenangan, tapi semua seperti pasir yang lolos dari genggaman.
Malam-malam semakin buruk. Amara mulai mengalami mimpi buruk yang jelas. Bukan kenangan, tapi gambaran-gambaran aneh: koridor gelap tak berujung, suara dengungan statis, dan siluet-siluet tinggi tanpa wajah.
Ia sering terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Bekas luka di pergelangan tangannya terasa panas. Amara menggaruknya tanpa sadar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah kulitnya.
Arya mulai memasang kamera pengawas di rumah. Bukan karena tak percaya pada Amara, tapi karena ada ketakutan yang merayapi hatinya. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada putrinya saat mereka tidur.
Rekaman menunjukkan Amara berjalan mondar-mandir di malam hari, berbicara dengan udara kosong. Terkadang, ia akan berhenti di depan cermin, menatap bayangannya dengan tatapan yang bukan miliknya.
Suatu malam, rekaman menangkap Amara berbisik ke cermin. "Kamu siapa?" tanyanya pada bayangannya sendiri. "Aku… bukan kamu." Suaranya penuh keputusasaan.
Keluarga mulai merasakan keanehan yang lebih dalam. Amara tidak lagi menyukai warna favoritnya, biru. Ia tiba-tiba menyukai kopi hitam pekat, padahal dulu ia membenci kafein. Kebiasaan kecil yang terasa sangat janggal.
Lena menemukan buku harian lama Amara. Ia membacanya, berharap menemukan petunjuk. Tulisan tangan itu sama, tapi isinya… sebagian besar adalah coretan tak bermakna, simbol-simbol aneh yang berulang.
Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang berbeda, lebih rapi, seperti dipaksakan. "Ini bukan rumahku. Ini bukan duniaku." Dan di bawahnya, sebuah simbol yang Amara gambar berulang kali di dinding kamarnya.
Simbol itu seperti jaring laba-laba yang rumit, namun dengan inti yang bersinar samar. Amara sering menggambarnya di mana-mana, di kertas, di meja, bahkan di telapak tangannya.
Dokter Friska menyarankan hipnosis. Mungkin dengan itu, Amara bisa mengakses kenangan yang terkunci. Amara setuju, putus asa ingin memahami dirinya sendiri.
Di bawah hipnosis, Amara mulai berbicara. Suaranya berubah, menjadi lebih dalam, lebih dingin. Ia berbicara tentang cahaya, tentang "mereka" yang mengambilnya, tentang sebuah "percobaan".
"Mereka mengubahku," bisik suara itu, bukan lagi suara Amara yang asli. "Mereka menanamkan sesuatu."
Friska bertanya, "Apa yang mereka tanamkan?"
"Ingatan. Tapi bukan ingatanku. Sebuah… peta."
Tiba-tiba, Amara menjerit. Tubuhnya kejang. Ia terbangun, napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak ketakutan. "Aku tahu!" teriaknya. "Aku tahu mengapa semuanya salah!"
Ia berlari ke kamar mandi, meraih cermin. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bayangannya. "Kamu bukan aku," katanya, air mata mengalir. "Aku bukan kamu."
Ia menunjuk ke lukisan abstrak di kamarnya. "Itu… itu adalah peta!"
Arya dan Lena masuk, bingung. "Peta apa, sayang?"
"Peta menuju… ke sana," Amara menunjuk ke luar jendela, ke langit malam. "Ke tempat mereka membawaku."
Ia mulai mencoret-coret di dinding dengan jarinya, mengulang simbol jaring laba-laba itu. "Ini gerbangnya," bisiknya, matanya terpaku pada simbol itu. "Mereka mengirimku kembali, tapi aku… aku bukan Amara."
Lena dan Arya hanya bisa menatap putri mereka, yang kini tampak asing, bahkan menakutkan. Kehadirannya di rumah itu terasa seperti invasi, sebuah misteri yang perlahan merusak realitas mereka.
Amara tidak pulang. Ia dikirim kembali. Sebuah wadah kosong, diisi dengan ingatan yang salah, sebuah peta menuju ketidaktahuan. Dan kengerian terbesar adalah kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah tahu, siapa sebenarnya yang kini berdiri di antara mereka.
Amara yang asli, di mana dia? Apakah ia masih ada, ataukah hanya kenangan usang? Dan entitas apa yang kini menempati tubuh yang mereka kenal sebagai putri mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan tak terjawab, seiring malam semakin gelap.