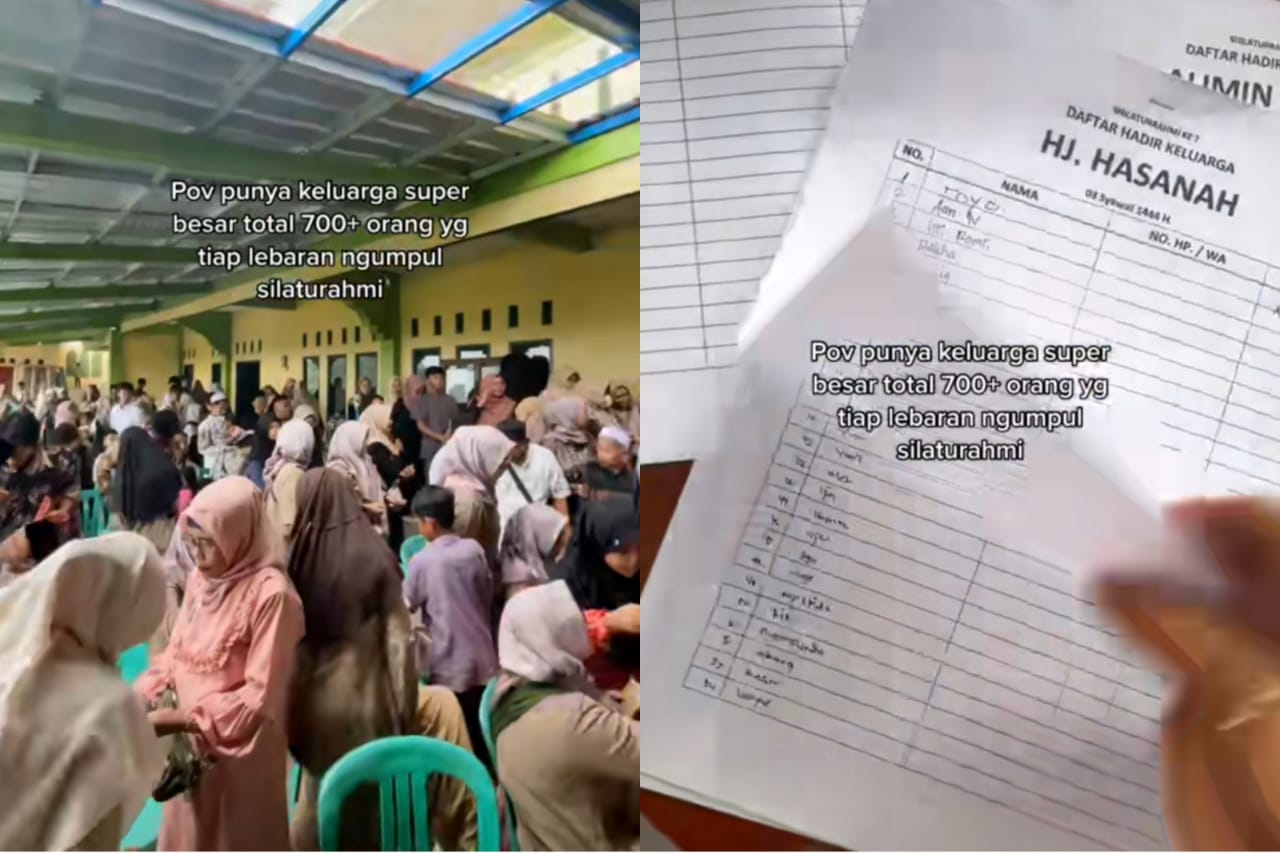Bayangan Siluman di Balik Petilasan: Rahasia Tirani yang Terkubur
Desir angin dingin menyelimuti bukit terpencil, tempat Petilasan Kerta Buana berdiri sunyi. Bangunan kuno itu, terbuat dari susunan batu hitam lumut, telah lama ditinggalkan. Kisah-kisah seram selalu menyertai namanya, bisikan tentang bayangan siluman yang bersemayam di baliknya.
Aku, Raka, seorang peneliti sejarah yang skeptis, selalu tertarik pada legenda. Petilasan Kerta Buana adalah target penelitianku selanjutnya, sebuah situs yang konon menyimpan rahasia kelam seorang raja tiran. Penduduk desa sekitar selalu memperingatkanku, mata mereka memancarkan ketakutan yang nyata.
"Jangan sentuh petilasan itu, Nak," ujar seorang tetua desa, suaranya bergetar. "Ada yang menjaga di sana, sesuatu yang bukan dari dunia kita. Dia tidak suka diganggu."
Aku hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai takhayul belaka. Bagiku, itu hanyalah cerita rakyat yang dibumbui imajinasi liar. Penasaran justru kian menguat, memacuku untuk membuktikan bahwa semua itu hanya isapan jempol.
Malam pertama di dekat petilasan, aku mendirikan tenda tak jauh dari pagar batunya. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan sabit yang sesekali mengintip di balik awan tebal. Hawa dingin merayap, menembus jaket tebal yang kukenakan.
Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh. Desiran halus, seperti kain sutra yang terseret di atas batu. Aku menajamkan pendengaran, jantung berdebar tak karuan. Suara itu berasal dari arah petilasan.
Perlahan, aku meraih senter dan keluar dari tenda. Gelap gulita menelan segalanya, hanya siluet pohon-pohon tua yang menjulang seperti jemari raksasa. Suara desiran itu semakin jelas, diikuti bisikan samar yang tak berbentuk.
Bulu kudukku meremang, namun rasa ingin tahu lebih dominan. Aku melangkah mendekat, senter kuarahkan ke arah petilasan. Cahaya putih menari di permukaan batu, menyingkap ukiran-ukiran purba yang nyaris tak terlihat.
Tiba-tiba, senterku berkedip-kedip lalu mati total. Kegelapan pekat menelanku, dan suara desiran itu kini terdengar tepat di belakangku. Napas dingin menerpa tengkuk, disusul aroma amis yang menusuk hidung.
Aku membalikkan badan, namun tak ada apa-apa. Hanya kehampaan dan keheningan yang mencekam. Jantungku berpacu gila, keringat dingin membasahi pelipis. Aku bergegas kembali ke tenda, mencoba menenangkan diri.
Keesokan harinya, aku kembali ke petilasan dengan bekal yang lebih lengkap. Kali ini, aku membawa kamera infra-merah dan alat perekam suara. Aku bertekad untuk menangkap bukti, menyingkap misteri di balik cerita-cerita itu.
Saat siang hari, petilasan itu tampak biasa saja, meski aura kuno dan sunyi tetap terasa. Aku mengamati setiap sudut, mencatat detail ukiran dan tata letak bangunan. Tak ada tanda-tanda keanehan.
Namun, saat senja mulai merayap, suasana berubah drastis. Bayangan memanjang memenuhi halaman petilasan, dan hawa dingin kembali datang, kali ini lebih pekat. Kamera infra-merahku mulai menunjukkan fluktuasi suhu yang aneh.
Ada titik-titik dingin yang bergerak sendiri, melayang di udara, seolah ada sesuatu tak kasat mata yang melintas. Alat perekam suaraku juga menangkap gelombang frekuensi rendah yang tak biasa, seperti dengungan dalam.
Aku merasa diawasi. Setiap gerakan terasa berat, seolah ada tekanan tak terlihat di sekelilingku. Aku mulai merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah ketakutan primal yang menggerogoti nalar.
Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di tenda, memantau petilasan dari kejauhan. Sekitar pukul dua dini hari, sebuah fenomena yang takkan pernah kulupakan terjadi.
Di tengah halaman petilasan, di antara pilar-pilar batu yang menjulang, sebuah bayangan mulai terbentuk. Bukan bayangan pohon atau awan, melainkan siluet hitam pekat yang perlahan memadat. Bentuknya menyerupai manusia, namun lebih tinggi, lebih ramping, dan tanpa detail wajah.
Bayangan itu bergerak. Perlahan, seolah melayang di atas tanah, mendekati salah satu pilar utama. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Itu dia, siluman yang dibicarakan!
Bayangan itu berhenti di depan pilar, dan dari kegelapan pekatnya, muncul dua titik merah menyala, seperti mata yang memancarkan kebencian abadi. Aku merasakan desakan energi yang luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik napasku.
Aku tak bisa berteriak, tak bisa lari. Aku terpaku, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Bayangan itu kemudian mengangkat tangannya yang panjang, tak berbentuk, dan menyentuh ukiran di pilar. Seketika, ukiran itu berpendar, memancarkan cahaya biru redup.
Terlintas dalam pikiranku, legenda tentang Prabu Angkara, raja tiran yang kejam. Konon, ia memiliki kekuatan gelap dan mengikat jiwanya pada petilasan ini untuk melindungi harta dan rahasia terlarangnya. Apakah bayangan itu adalah jiwanya yang terperangkap?
Aku memberanikan diri, mengarahkan kamera ke arah bayangan itu. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol rekam. Aku harus mendapatkan bukti, harus mengungkap kebenaran di balik kegelapan ini.
Namun, seolah menyadari keberadaanku, bayangan itu menoleh. Titik-titik merah itu kini menatap lurus ke arahku, seolah menembus kegelapan dan melihat jiwaku. Sebuah jeritan tak berbentuk terdengar di telingaku, bukan suara, melainkan getaran mengerikan yang membuat kepalaku pening.
Aku menjatuhkan kamera, tubuhku ambruk ke tanah. Pandanganku kabur, dan aku merasakan dingin yang luar biasa, bukan dingin suhu, melainkan dingin kematian yang merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun.
Dalam kebingungan, aku melihat bayangan itu mendekat. Langkahnya tak bersuara, namun setiap gerakannya mengirimkan gelombang teror. Ia menjulang di atasku, menutupi cahaya rembulan yang samar.
Mata merah itu kini begitu dekat, aku bisa melihat pusaran kebencian di dalamnya. Aku mendengar bisikan, ribuan suara yang tumpang tindih, mengutuk, menangis, dan meraung. Itu adalah suara penderitaan, suara ribuan jiwa yang mungkin telah menjadi korban Prabu Angkara.
Aku yakin ini adalah akhirku. Namun, tepat saat bayangan itu mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuhku, sebuah suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan.
Seketika, bayangan itu bergetar hebat. Titik-titik merah di matanya meredup, dan bentuknya mulai memudar. Jeritan tak berbentuk itu berubah menjadi desahan putus asa, lalu menghilang bersamaan dengan datangnya cahaya fajar.
Aku terbaring lemah, napas tersengal-sengal. Tubuhku gemetar tak terkendali, dan air mata mengalir tanpa kusadari. Aku telah melihatnya, aku telah merasakan kehadirannya. Bayangan siluman itu nyata.
Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku terbangun di tendaku, matahari sudah tinggi. Kameraku tergeletak di samping, layarnya retak. Aku memeriksa rekaman, namun yang kutemukan hanyalah rekaman gelap dan suara statis yang mengerikan.
Aku meninggalkan Petilasan Kerta Buana hari itu juga, tanpa menoleh ke belakang. Penelitianku tentang Prabu Angkara dan petilasannya belum selesai, namun aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke sana sendirian.
Kisah tentang bayangan siluman di balik petilasan itu kini bukan lagi legenda bagiku. Itu adalah kenyataan pahit yang menghantuiku. Aku tahu, di balik dinding batu yang sunyi itu, rahasia tirani masih terkubur, dijaga oleh entitas yang terperangkap dalam kegelapan abadi.
Dan setiap kali angin malam berdesir, aku bisa merasakan dinginnya, seolah bayangan itu masih membuntutiku, sebuah peringatan akan kejahatan masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Petilasan Kerta Buana akan selamanya menjadi misteri kelam, sebuah penjara bagi jiwa yang terikat pada kegelapan.