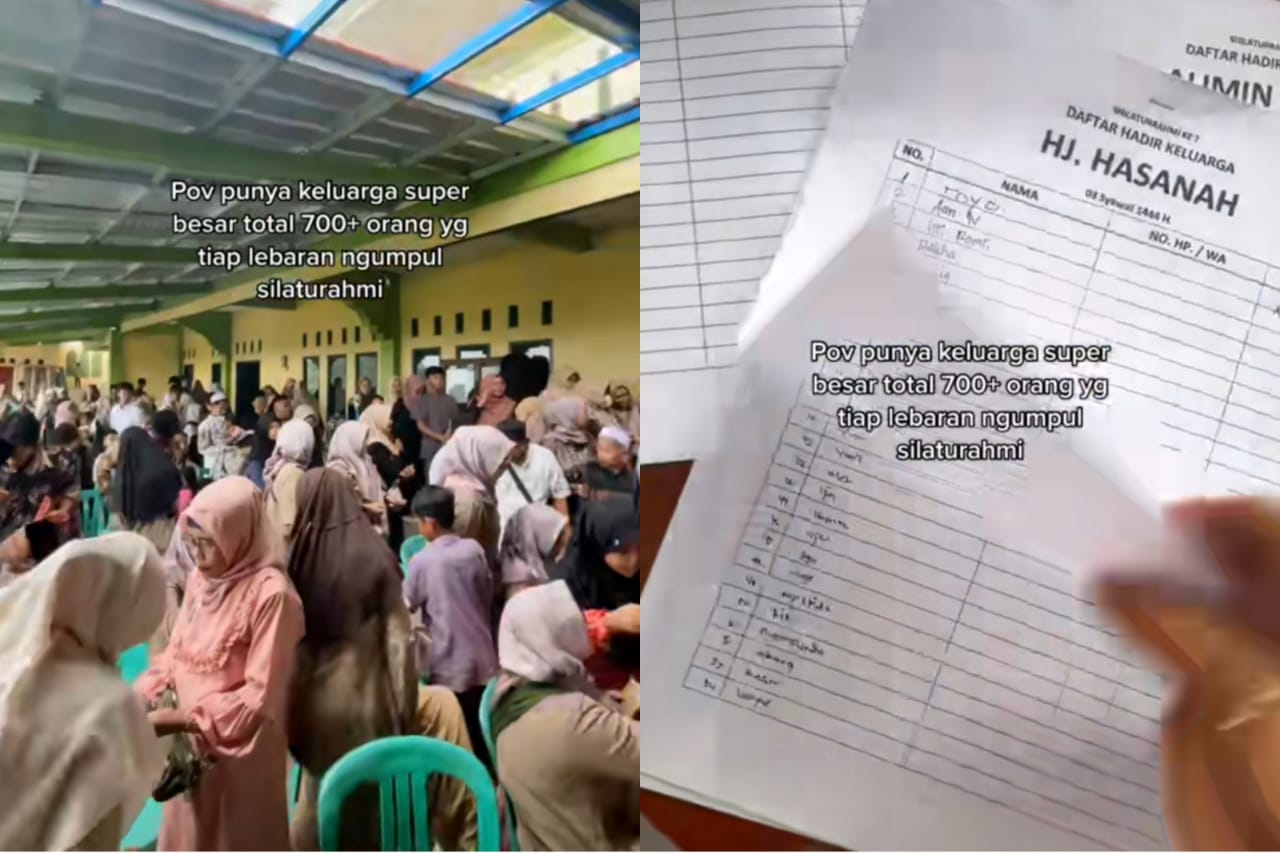Udara di gang sempit itu selalu terasa lembap dan berat. Dinding-dinding kusam gang kos "Senja Kelabu" seolah menyimpan bisikan tak terucap dari setiap penghuninya. Namun, ada satu bisikan yang jauh lebih pekat, melayang di sekitar Kamar Nomor Tujuh.
Kamar itu, menurut desas-desus, tak pernah dihuni lebih dari seminggu. Setiap penyewa baru datang dengan harapan, namun pergi dengan wajah pucat pasi, tak pernah lagi menoleh ke belakang.
Arga, seorang mahasiswa perantauan yang terlilit krisis finansial, mendengar semua cerita itu. Ia mendengar tentang hawa dingin yang menusuk, bisikan tanpa sumber, dan bayangan yang melintas di ambang penglihatan.
"Kamar itu murah, Nak," ujar Pak Broto, pemilik kos yang sudah tua, matanya menyiratkan kelelahan. "Tapi aku sudah memperingatkanmu. Banyak yang tak tahan."
Arga hanya tersenyum skeptis. "Saya tidak percaya takhayul, Pak. Mungkin hanya perbaikan gedung yang kurang memadai." Ia berpikir, harga sewa yang nyaris tak masuk akal adalah tawaran yang tak bisa ditolak.
Malam pertama di Kamar Nomor Tujuh, Arga merapikan barang-barangnya. Suasana kamar memang terasa lebih sejuk dibanding ruangan lain, padahal jendela tertutup rapat. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya karena lokasi kamar yang agak tersembunyi.
Hanya ada satu jendela kecil menghadap ke tembok tetangga, membatasi pandangan dunia luar. Dinding-dinding berwarna krem pucat terasa lembap di sentuhan jemari. Udara dingin seperti merayap dari lantai.
Jam menunjukkan pukul dua dini hari. Arga terbangun dari tidur singkatnya. Sebuah bisikan samar terdengar, seperti hembusan napas di dekat telinganya. "Sendiri…"
Ia tersentak, bangkit duduk. Kamar gelap gulita, hanya diterangi rembulan yang menerobos tirai tipis. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, "Pasti cuma mimpi," gumamnya, mencoba meyakinkan diri.
Pagi kedua, segalanya terasa normal. Arga berangkat kuliah, melupakan kejadian semalam. Namun, saat kembali sore harinya, ia merasakan perubahan kecil yang mengganggu.
Sebuah buku yang ia letakkan di meja belajar kini berada di lantai, persis di samping kakinya. Ia yakin sekali meletakkannya dengan rapi. "Angin?" ia mencoba beralasan, meskipun jendela tertutup rapat.
Malam kedua, hawa dingin semakin terasa. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, seperti embusan es dari dalam dinding. Arga menarik selimutnya sampai ke leher.
Terdengar suara ketukan lembut, teratur, dari dalam lemari pakaian tua di sudut kamar. Tuk. Tuk. Tuk. Jantung Arga berdebar. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih seksama.
Suara itu berhenti. Arga memberanikan diri. Dengan ponsel sebagai senter, ia perlahan mendekati lemari. Ia membuka pintunya. Kosong. Hanya tumpukan pakaiannya yang baru ia letakkan.
Tidak ada yang mencurigakan. Ia menutup lemari, namun saat membalikkan badan, ia merasa seperti ada hembusan napas dingin di belakang lehernya. Ia berbalik cepat, namun tak ada apa-apa.
Hari ketiga, Arga mulai merasa terganggu. Kantung matanya menghitam. Konsentrasinya buyar di kampus. Ia seringkali melamun, memikirkan kejadian-kejadian di kamar itu.
Ia pulang ke kos lebih awal, ingin menghadapi apa pun yang ada di sana. Ia duduk di kasur, mengamati setiap sudut kamar. Kamar itu terasa sunyi, namun juga dipenuhi ketegangan tak terlihat.
Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga suram, hawa dingin di kamar semakin pekat. Udara di sekelilingnya terasa berat, menekan dadanya.
Sebuah bayangan tipis melintas di ambang pintu kamar mandi, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Arga menoleh, memicingkan mata, namun tak ada apa-apa. "Ini konyol," ia bergumam, mencoba menepis rasa takut.
Malam ketiga adalah puncaknya. Saat Arga memejamkan mata, ia mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mendesak. "Jangan… tinggalkan… aku…"
Ia membuka mata, namun kamar itu masih gelap gulita. Tidak ada wujud. Hanya suara itu, seperti berasal dari dalam benaknya sendiri, namun begitu nyata. Ia tidak bisa tidur.
Hari keempat, Arga tampak seperti zombie. Ia menghindari teman-temannya, takut mereka akan melihat kegelisahan di matanya. Ia bahkan tidak makan dengan benar.
Ia mencoba mencari informasi tentang Kamar Nomor Tujuh. Ia bertanya pada penghuni kos lain, namun mereka hanya menggelengkan kepala, menyuruhnya pindah secepatnya.
"Ada yang bilang dulu ada mahasiswi meninggal di kamar itu," bisik seorang penghuni lama. "Bunuh diri karena putus cinta. Tapi itu sudah lama sekali."
Arga mencoba mencari arsip berita lama di perpustakaan kampus. Tidak ada catatan tentang kematian di kos "Senja Kelabu." Cerita itu mungkin hanya legenda.
Namun, semakin ia mencari, semakin kuat pula keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hantu yang jahat, melainkan sesuatu yang tersisa, tertinggal di sana.
Malam keempat, bau melati yang pekat tiba-tiba menyelimuti kamar. Bau itu manis, namun juga menyesakkan, seperti aroma kematian yang disamarkan. Arga mual.
Lampu kamar berkedip-kedip, kemudian padam sama sekali. Kamar itu gelap gulita. Arga merasakan napas dingin menyapu tengkuknya, diikuti bisikan yang kali ini jelas dan pedih.
"Dingin… sendiri… kenapa… kau pergi…?"
Arga melompat dari kasur, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia menyalakan senter ponselnya, mengarahkan ke setiap sudut. Tidak ada.
Ia menyadari, suara itu bukan hanya bisikan di telinganya. Itu adalah suara yang merayap di dalam jiwanya, membawa serta kesedihan dan keputusasaan yang mendalam.
Hari kelima, Arga tidak sanggup lagi tidur di kamar itu. Ia menghabiskan malam di perpustakaan kampus, berpura-pura belajar. Namun, bayangan Kamar Nomor Tujuh terus menghantuinya.
Ia kembali ke kos hanya untuk mandi dan berganti pakaian. Saat membuka pintu kamar, ia merasakan tatapan tajam yang tak terlihat, seolah ada seseorang yang menunggunya di dalam.
Ia melihat bayangan samar di cermin lemari, terlalu cepat untuk ia tangkap. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang terurai, kepalanya menunduk.
Arga menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu ia tidak sendirian di kamar itu. Ada sesuatu yang ingin ia lihat, sesuatu yang ingin ia rasakan.
Malam keenam, Arga memutuskan untuk menghadapi apa pun yang ada. Ia membawa sebuah kamera perekam kecil dan meletakkannya di sudut kamar. Ia ingin bukti.
Ia duduk di kasur, membiarkan kegelapan menyelimutinya. Hawa dingin semakin menggigit. Bau melati semakin kuat, memenuhi rongga hidungnya hingga ia sulit bernapas.
Tiba-tiba, sebuah suara tangisan pilu terdengar. Bukan tangisan manusia, melainkan tangisan yang dipenuhi kesedihan tak berujung, seperti ratapan dari lubuk hati yang paling dalam.
Arga merinding. Ia melihat ke arah jendela. Ada bayangan putih tipis yang melayang di sana, perlahan membentuk siluet seorang wanita. Wanita itu membelakanginya.
Ia mengangkat tangannya, seolah ingin meraih sesuatu. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jernih, lebih menyayat hati. "Aku… sendirian… kenapa… kau pergi…?"
Bayangan itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan basah oleh air mata. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang tak terkatakan.
Arga tak bisa bergerak. Ia terpaku, menatap wajah itu, wajah yang dipenuhi kepedihan dan pengkhianatan. Ia merasakan kesedihan yang sama merayapi hatinya.
Wanita itu perlahan mengangkat tangannya yang transparan, menunjuk ke arahnya, namun tatapannya menembus Arga, seolah melihat sesuatu di baliknya.
Kemudian, ia melihat adegan itu. Seperti sebuah rekaman yang diputar ulang. Wanita itu, Laras, terhuyung-huyung di dalam kamar. Air mata membasahi pipinya. Ia memegang sepucuk surat.
Surat itu jatuh dari tangannya. Laras merosot ke lantai, menangis pilu. Ia memeluk lututnya, punggungnya bergetar hebat. Kamar itu dipenuhi keputusasaan.
Arga menyaksikan Laras perlahan-lahan memudar, menjadi semakin transparan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Tangisannya mereda, hanya menyisakan gema kesedihan di udara.
Pagi ketujuh, Arga terbangun dengan perasaan hampa. Ia tidak lari, tidak berteriak. Ia hanya merasa lelah, dan sedih. Ia mengerti mengapa tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu.
Kamar itu bukan dihuni oleh hantu yang jahat, melainkan oleh jejak kesedihan dan keputusasaan yang begitu pekat. Ia adalah kenangan abadi dari Laras, yang meninggal karena patah hati di sana.
Setiap penghuni baru merasakan beban emosional itu, merasakan sakit Laras yang tak terobati. Mereka tidak lari karena takut, melainkan karena tidak sanggup menanggung kesedihan yang begitu dalam.
Arga berkemas. Ia tak lagi skeptis. Ia tahu kebenaran Kamar Nomor Tujuh. Ia menyerahkan kunci kepada Pak Broto yang tampak sudah menduganya.
"Kau juga tidak tahan, Nak?" tanya Pak Broto lirih. Arga hanya mengangguk, matanya menatap Kamar Nomor Tujuh dengan pandangan penuh pengertian.
"Bukan tidak tahan, Pak," jawab Arga pelan. "Hanya saja, saya tidak sanggup menanggung kesedihan seseorang yang begitu dalam. Kamar itu… terlalu sedih."
Pak Broto hanya menghela napas panjang. Kamar Nomor Tujuh kembali kosong. Menunggu penyewa baru yang penuh harapan, yang akan merasakan kesedihan Laras, dan pergi lagi sebelum seminggu berakhir.
Bisikan "Sendiri…" akan terus melayang di kamar itu, sebuah elegi abadi tentang patah hati dan kehilangan. Kamar itu, bukan dihuni oleh roh pendendam, melainkan oleh duka yang tak pernah usai.