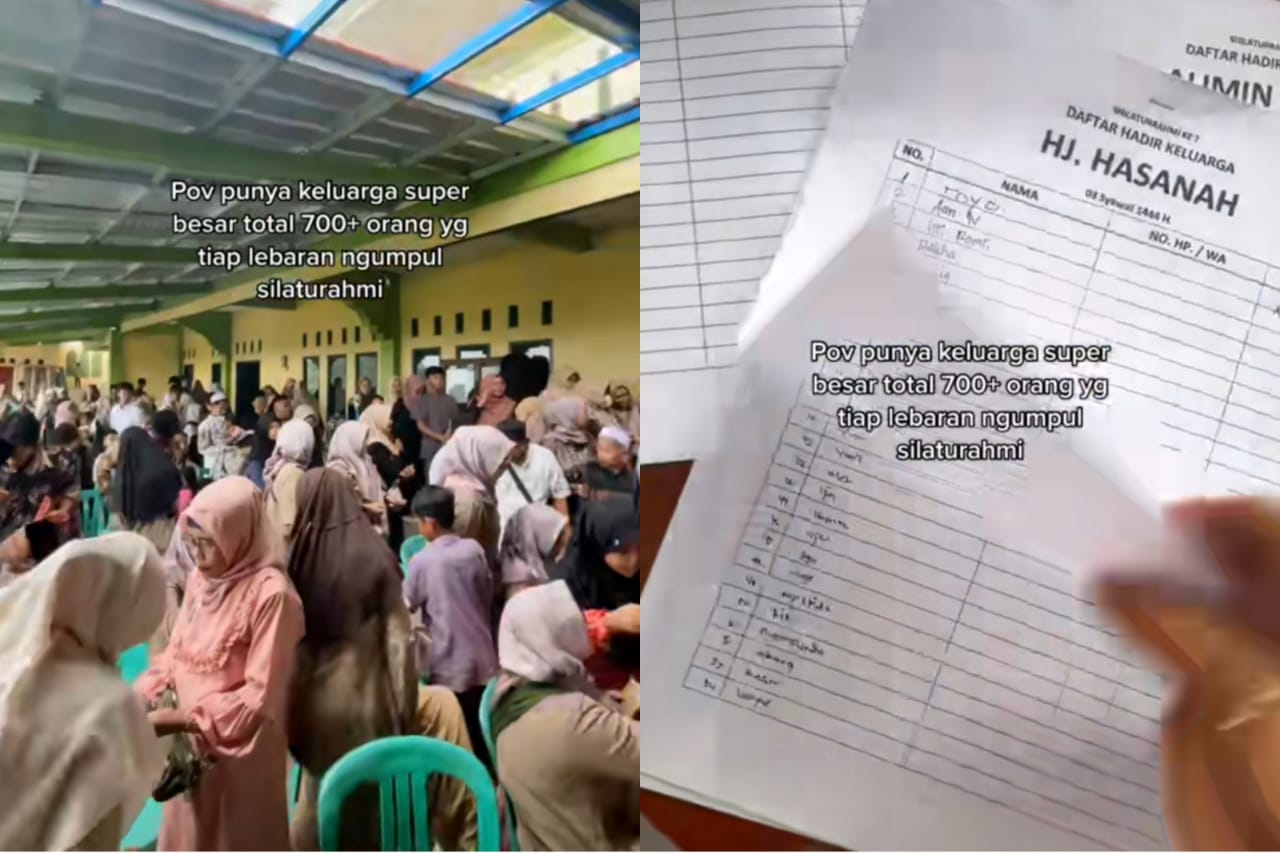Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya hutan jati, tradisi Kuda Lumping masih hidup kuat. Malam itu, purnama penuh menggantung rendah di langit. Udara dingin mulai merayap, membawa aroma tanah basah dan kembang melati. Penduduk desa berkumpul di lapangan, menanti dimulainya pertunjukan.
Alunan gamelan perlahan mengalun, membelah keheningan malam. Dentuman kendang mulai menguasai suasana. Para penari Kuda Lumping, dengan pakaian warna-warni dan jaran kepang bambu mereka, mulai bergerak. Gerakan mereka ritmis, memukau, seolah memanggil entitas tak kasat mata.
Ritual trance adalah inti dari Kuda Lumping. Para penari akan kesurupan. Mereka melahap pecahan kaca, memakan padi, atau menggigit kelapa utuh. Semua dilakukan di bawah kendali seorang pawang. Pawang itu memiliki tatapan tajam dan mantra-mantra kuno yang berbisik.
Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Desir angin seolah membawa bisikan tak kasat mata. Cahaya obor tampak menari-nari tak menentu, menciptakan bayangan aneh di antara kerumunan. Sebuah firasat buruk mulai merayap di hati beberapa orang.
Seorang penari tua, Mbah Karto, merasa gelisah. Dahinya berkerut. Matanya tak lepas dari sebuah jaran kepang yang tergeletak di sudut panggung. Jaran kepang itu belum dipakai. Ia terbuat dari anyaman bambu dan kulit kuda. Warnanya hitam pekat.
Jaran kepang hitam itu tampak berkedut. Sebuah gerakan halus, hampir tak terlihat. Mbah Karto menggosok matanya. Ia mengira itu hanya ilusi optik. Namun, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal.
Gamelan semakin cepat, iramanya kian memacu adrenalin. Para penari mulai memasuki fase puncak trance mereka. Mereka berteriak, menggeram, dan bergerak liar. Suasana mencekam namun memukau menyelimuti lapangan.
Tiba-tiba, mata Mbah Karto membelalak. Jaran kepang hitam itu bergerak lagi. Kali ini, lebih jelas. Ia sedikit terangkat dari tanah. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada angin kencang yang lewat.
Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara penonton. Beberapa orang menunjuk ke arah jaran kepang itu. Wajah-wajah mulai memucat. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menyebar. Pertunjukan sejenak terhenti.
Jaran kepang itu kini berdiri tegak. Perlahan, ia mulai bergerak. Langkahnya kaku, namun pasti. Ia melangkah maju, seolah ada penunggang tak terlihat di punggungnya. Suara “thump-thump” dari kaki bambunya memecah keheningan.
Para penari yang sedang trance pun terdiam. Mereka terpaku, mata mereka memandang kosong ke arah jaran kepang hitam. Pawang pun terlihat kaget. Ia mencoba memanggil mantra. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan.
Jaran kepang itu terus bergerak. Ia menari-nari di tengah lapangan. Gerakannya semakin lincah, tak ubahnya penari Kuda Lumping sungguhan. Namun, ia kosong. Ia tak berpenunggang. Sebuah kekosongan yang menari.
Ketakutan melanda kerumunan. Teriakan tertahan mulai terdengar. Beberapa orang tua mulai membacakan doa-doa. Mereka menyadari, ini bukan bagian dari pertunjukan. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyeramkan.
“Itu… bukan penari kita,” bisik seorang wanita tua. Suaranya bergetar. “Itu entitas lain. Ia datang.”
Jaran kepang hitam itu kini mengelilingi pawang. Ia menari mengitari pria tua itu. Gerakannya semakin cepat. Matanya, yang tadinya hanya lubang kosong, kini seolah memancarkan cahaya merah samar. Sebuah tatapan tanpa bola mata.
Pawang itu jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Mantra-mantranya seolah tak berarti di hadapan kekuatan ini. Ia tahu, ia telah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua. Jauh lebih kuat.
Jaran kepang itu berhenti tepat di depan pawang. Ia menunduk. Seolah membungkuk memberi hormat. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan suara ringkikan. Ringkikan itu bukan suara kuda. Itu adalah suara tawa. Tawa yang mengerikan.
Tawa itu membuat bulu kuduk berdiri. Para penonton berhamburan. Mereka berlari ke segala arah. Mereka ingin menjauh dari makhluk itu. Mereka ingin lari dari misteri yang tiba-tiba merayap di malam itu.
Namun, jaran kepang itu tak mengejar. Ia hanya berdiri. Ia memandangi kerumunan yang panik. Lalu, ia kembali menari. Ia menari dengan liar, dengan gerakan yang tak mungkin dilakukan oleh sebuah benda mati.
Ia melompat tinggi, melayang sejenak di udara. Kemudian ia berputar-putar. Ia seperti merayakan kekacauan yang diciptakannya. Sebuah pertunjukan horor yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Tiba-tiba, jaran kepang itu berhenti mendadak. Ia membeku di tengah tarian. Cahaya merah di matanya memudar. Ia kembali menjadi benda mati. Ia kembali menjadi jaran kepang bambu dan kulit kuda yang kosong.
Keheningan kembali melanda lapangan. Hanya napas terengah-engah dari mereka yang masih tersisa yang terdengar. Lapangan itu kini kosong. Hanya jaran kepang hitam itu yang tergeletak di sana. Sendiri.
Mbah Karto perlahan mendekat. Kakinya bergetar. Ia menyentuh jaran kepang itu. Dingin. Mati. Tak ada sisa-sisa kekuatan yang tadi terpancar. Seolah semua hanya mimpi buruk yang berlalu begitu saja.
Namun, semua orang tahu, itu bukan mimpi. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sebuah jaran kepang menari sendiri. Sebuah entitas tak dikenal telah menampakkan diri.
Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Suasana mencekam selalu menyelimuti. Para tetua desa sering berkumpul. Mereka membicarakan hal itu. Mereka mencoba mencari tahu. Siapa atau apa yang telah datang?
Ada yang mengatakan itu adalah arwah leluhur yang marah. Ada pula yang percaya itu adalah jin penunggu hutan yang tersinggung. Namun, tak ada yang tahu pasti. Misteri itu tetap tak terpecahkan.
Jaran kepang hitam itu disimpan di rumah Mbah Karto. Ia tak berani menyentuhnya lagi. Ia hanya menatapnya dari kejauhan. Sebuah pengingat akan malam yang mengerikan itu. Malam ketika batas antara dunia nyata dan gaib menipis.
Sesekali, di malam-malam tertentu, Mbah Karto mengaku mendengar suara ringkikan samar. Suara itu datang dari kamar tempat jaran kepang itu disimpan. Suara tawa yang menakutkan. Suara yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak.
Misteri jaran kepang yang bergerak sendiri itu menjadi legenda di desa itu. Sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan. Bahwa ada kekuatan di luar pemahaman manusia. Kekuatan yang bisa muncul kapan saja.
Dan di balik setiap pertunjukan Kuda Lumping, di setiap alunan gamelan dan setiap hentakan kaki penari, selalu ada bisikan. Bisikan tentang jaran kepang hitam. Bisikan tentang entitas yang menunggu kesempatan. Untuk menari lagi. Sendiri.
Kisah itu mengajarkan bahwa di balik keindahan seni tradisional, tersimpan rahasia yang dalam. Rahasia yang lebih tua dari ingatan. Rahasia yang dapat membangkitkan rasa takut. Dan meninggalkan jejak misteri.
Hingga kini, di desa itu, setiap kali pertunjukan Kuda Lumping digelar, selalu ada tatapan mata yang penuh waspada. Menatap ke sudut panggung. Mencari. Apakah jaran kepang hitam itu akan bergerak lagi?
Ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia bersembunyi di balik senyum ramah penduduk desa. Ia tersimpan di setiap cerita rakyat yang diturunkan. Menanti malam yang tepat. Untuk kembali menampakkan diri.
Kuda Lumping, sebuah seni yang memukau, kini juga menjadi simbol. Simbol akan batas tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Batas yang bisa terlampaui. Kapan saja. Oleh siapa saja. Atau oleh apa saja.
Dan di tengah keheningan malam, terkadang, kau bisa mendengar. Suara ringkikan. Suara tawa. Tawa dari jaran kepang yang bergerak sendiri. Mengingatkanmu. Bahwa beberapa misteri, lebih baik tetap menjadi misteri.
Karena jika kau terlalu dalam mencari jawabannya, mungkin kau akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang tak ingin kau temukan. Sesuatu yang akan menghantuimu. Selamanya. Seperti jaran kepang hitam itu.