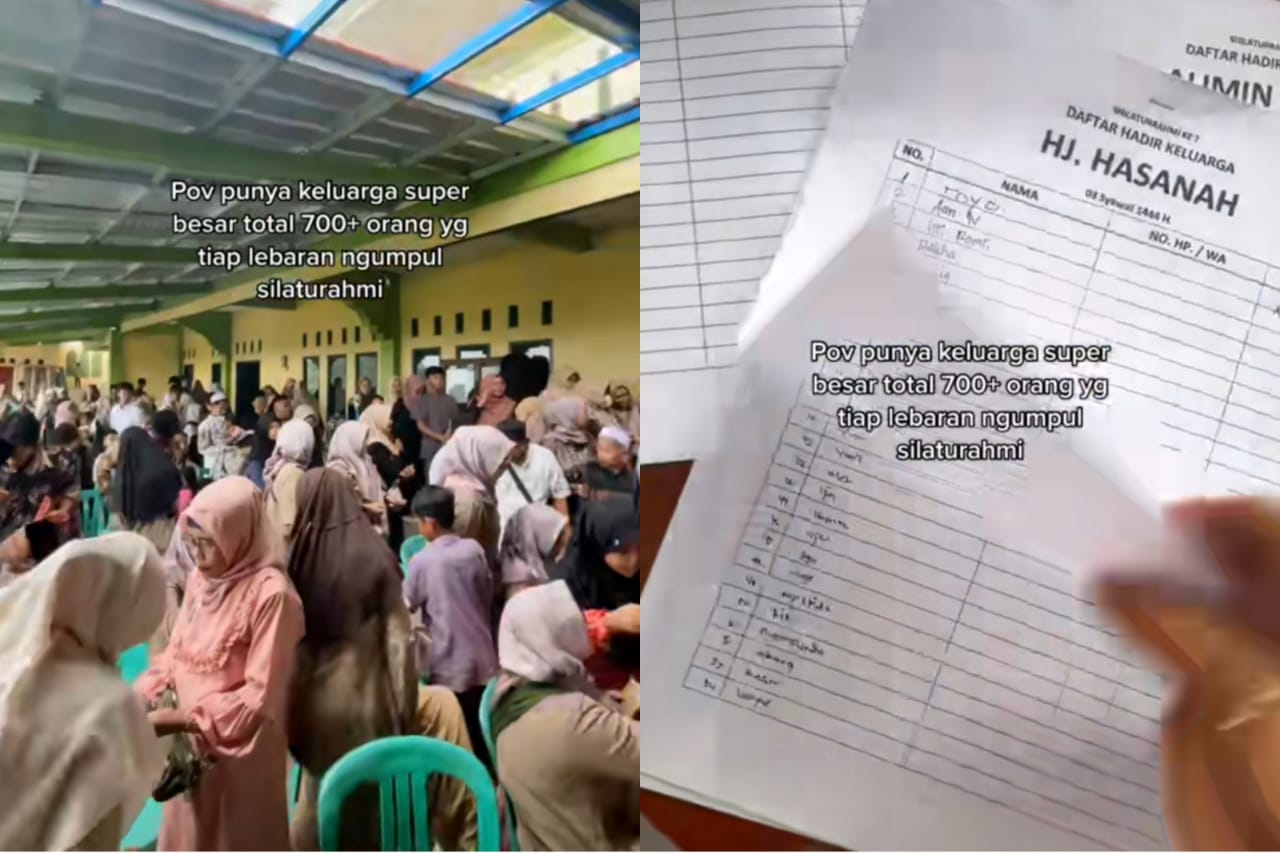
Rumah Terbuka di Tengah Lampor: Sebuah Undangan dari Kegelapan
Malam itu, angin berbisik dingin, membawa serta aroma tanah basah dan ketakutan purba. Sebuah undangan aneh tiba di meja saya, tercetak di kertas tua dengan tinta nyaris pudar. "Rumah Terbuka: Mengamati Lampor Lewat."
Saya, seorang jurnalis skeptis, mengernyitkan dahi. Lampor, pawai arwah gentayangan yang membawa wabah dan kematian, adalah legenda yang tak saya percaya. Mengapa ada yang menggelar acara di tengah kengerian itu?
Alamatnya adalah rumah tua di pinggir kota, yang selalu diselimuti aura misteri. Konon, rumah itu berdiri di atas tanah kuno, tempat persemayaman roh-roh tak tenang. Undangan itu seperti ejekan terhadap akal sehat.
Namun, rasa penasaran mengalahkan nalar. Saya tiba di sana tepat sebelum senja merangkak pergi. Gerbang besi berkarat terbuka sedikit, mengundang dengan desahan pelan.
Pekarangannya sepi, tak ada satupun mobil tamu. Hanya ada cahaya remang-remang dari dalam rumah, seolah memanggil saya masuk ke dalam jurang keheningan. Jantung saya berdebar tak karuan.
Seorang pria tua menyambut di ambang pintu, perawakannya kurus dengan senyum tipis yang tak bisa saya artikan. Matanya tajam, seolah menyimpan rahasia berabad-abad. "Selamat datang," sapanya. "Saya Pak Kartolo."
Ia adalah pemilik rumah, begitu ramah namun dengan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya melihat ada beberapa tamu lain di ruang tamu, sekitar lima atau enam orang, semuanya tampak sama bingungnya.
Mereka adalah kolektor barang antik, sejarawan lokal, dan seorang parapsikolog. Kami semua tergiur oleh janji Pak Kartolo untuk "pengalaman yang tak terlupakan" di malam Lampor.
Ruang tamu itu luas, dipenuhi furnitur kayu jati ukiran rumit. Patung-patung kuno dengan mata kosong seolah mengawasi dari setiap sudut. Udara terasa berat, pengap, dan berbau dupa lawas.
"Kita akan menyaksikan sebuah fenomena," kata Pak Kartolo dengan suara tenang, seraya menuangkan teh melati ke cangkir-cangkir antik. "Lampor tidak akan melukai mereka yang mengerti."
Kami saling pandang, mencoba memahami maksudnya. Beberapa tamu tampak gelisah, sementara yang lain mencoba mempertahankan ketenangan palsu. Saya sendiri merasakan firasat buruk yang terus merayap.
Malam semakin larut. Di luar, suara-suara kota perlahan mati. Hanya ada keheningan mencekam, diselingi derit bambu dan lolongan anjing dari kejauhan.
Pak Kartolo meminta kami untuk duduk di dekat jendela besar yang menghadap jalan. Jendela itu terbuat dari kaca tebal, namun entah mengapa, terasa transparan hingga ke jiwa.
"Waktunya semakin dekat," bisiknya, matanya menerawang ke luar. Suara anjing-anjing di kejauhan semakin histeris, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata.
Hawa dingin mulai menusuk tulang, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa kuno dan membawa kematian. Lilin-lilin di meja mulai berkedip-kedip liar, seolah ditarik oleh napas tak terlihat.
Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Desiran halus, seperti ribuan kaki telanjang menyeret di atas kerikil. Lalu, ada bisikan-bisikan, seperti gumaman dari kedalaman sumur tua.
Salah satu tamu, seorang sejarawan bernama Bu Lastri, mulai gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. "Itu… itu mereka," bisiknya, suaranya tercekat.
Pak Kartolo hanya tersenyum tipis. "Sabar, Nyonya. Ini baru permulaan." Senyumnya itu, entah mengapa, terasa lebih mengerikan daripada suara-suara di luar.
Kemudian, kami melihatnya. Cahaya-cahaya redup, berkedip-kedip di kejauhan, bergerak perlahan mendekat. Mereka bukan cahaya biasa, melainkan pendaran aneh yang memancarkan kengerian.
Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Obor-obor kuno yang dipegang oleh bayangan-bayangan menjulang tinggi. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa jejak, seperti hantu dari masa lalu.
Jantung saya berdetak kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin lepas. Rasa skeptis saya runtuh berkeping-keping, digantikan oleh teror murni yang membekukan.
Bayangan-bayangan itu mulai terlihat lebih jelas. Wajah-wajah pucat, mata cekung, kulit keriput seolah telah ribuan tahun di dalam kubur. Mereka semua menatap ke arah rumah.
Tepatnya, mereka menatap ke arah kami.
Salah satu tamu, seorang pemuda parapsikolog, mencoba berdiri. Kakinya goyah, ia terjatuh. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, matanya menatap horor ke arah jendela.
"Jangan bergerak," perintah Pak Kartolo, suaranya kini dingin dan tanpa emosi. "Mereka akan tahu jika kalian panik." Namun, suaranya sendiri terdengar seperti bisikan kematian.
Pawai Lampor kini berada tepat di depan rumah. Kami bisa melihat detail setiap sosok: pakaian compang-camping, rambut kusut, dan tangan-tangan kurus yang menggenggam obor.
Mereka berhenti. Ribuan pasang mata kosong menatap kami dari balik jendela. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, seolah es telah mengisi setiap pori-pori.
Seorang wanita dalam barisan Lampor, dengan rambut panjang terurai dan gaun putih kotor, mengangkat tangannya yang kurus. Jari telunjuknya menunjuk langsung ke arah kami.
Semua tamu terpaku, tak berani bernapas. Ketakutan itu begitu pekat, begitu nyata, hingga terasa seperti zat yang bisa disentuh. Kaca jendela bergetar pelan.
Tiba-tiba, suara retakan keras memecah keheningan. Salah satu kaca jendela retak, perlahan membentuk pola jaring laba-laba. Retakan itu seolah ditarik dari luar.
Dan melalui retakan itu, sebuah mata kosong mengintip. Sangat dekat. Sangat nyata. Bau anyir dan tanah kuburan menyengat hidung.
Kami semua menjerit, namun suara kami tertahan di tenggorokan. Semua orang berusaha mundur, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan kami di tempat.
Pak Kartolo masih berdiri tegak, senyumnya kini melebar menjadi seringai mengerikan. Matanya berkilat, memancarkan kepuasan yang membuat perut saya mual.
"Lihatlah mereka baik-baik," bisiknya, suaranya kini terdengar seperti gema dari masa lalu. "Mereka datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka."
Kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Salah satu sosok Lampor, yang paling depan, perlahan mengangkat tangannya. Obornya memancarkan cahaya biru aneh.
Cahaya itu menembus kaca jendela yang retak, langsung menuju ke arah pemuda parapsikolog yang terjatuh tadi. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya mengejang hebat.
Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai memudar. Seperti asap yang tertiup angin, ia menghilang, meninggalkan hanya bayangan samar di lantai dan bau busuk yang menyengat.
Para tamu lain menjerit histeris, kali ini suara mereka berhasil keluar. Mereka merangkak mundur, mencoba menjauh dari jendela, dari rumah terkutuk ini.
Pak Kartolo tertawa kecil. Tawa itu kering, menyeramkan, seperti suara daun-daun kering yang diinjak. "Sudah kubilang, mereka akan mengambil apa yang seharusnya."
"Apa yang kau lakukan?!" teriak saya, jantung saya berdegup gila. "Siapa kau sebenarnya?!"
Ia menatap saya, senyumnya masih terpampang. "Aku hanya pengamat. Dan sesekali, penyedia."
"Penyedia apa?!" desak saya, napas saya tersengal.
"Penyedia jiwa," jawabnya tenang, menunjuk ke arah Lampor yang kini mulai bergerak lagi. "Mereka lapar. Dan rumah ini… rumah ini adalah gerbangnya."
Pawai Lampor mulai bergerak menjauh, obor-obor mereka perlahan memudar di kejauhan. Keheningan kembali menyelimuti, namun kini keheningan itu terasa lebih menakutkan.
Bau busuk masih tertinggal, menjadi saksi bisu atas apa yang baru saja terjadi. Para tamu yang tersisa tergeletak di lantai, menangis, pingsan, atau menatap kosong.
Saya menatap Pak Kartolo. Wajahnya kembali tenang, senyumnya kembali tipis, seolah tak ada yang terjadi. Ia berjalan ke arah jendela, mengelus retakan kaca itu.
"Ini adalah undangan khusus," katanya, tanpa menoleh. "Undangan yang tak bisa ditolak. Kau tahu itu, kan?"
Saya tidak menjawab. Saya hanya bisa menatap bayangan samar di lantai tempat pemuda itu menghilang. Aroma kematian masih melekat di udara.
Rumah itu kini terasa seperti perangkap. Sebuah jebakan yang tersembunyi di balik undangan ramah. Dan kami, para tamu yang penasaran, adalah umpannya.
Pak Kartolo berbalik, menatap saya dengan tatapan yang membuat saya merasa telanjang dan rentan. "Sampai jumpa di Lampor berikutnya," bisiknya. "Mungkin kau yang akan menjadi bagian dari pawai."
Saya tidak pernah kembali ke rumah itu. Namun, setiap malam, ketika angin berbisik dingin, saya bisa mendengar desiran kaki-kaki tak terlihat.
Dan saya selalu bertanya-tanya, siapa yang akan menerima undangan "Rumah Terbuka" Pak Kartolo berikutnya. Dan siapa yang akan menjadi bagian dari pawai abadi Lampor.
Ketakutan itu tak pernah sirna. Ia tetap hidup, merayap dalam kegelapan, menunggu malam Lampor yang akan datang.






