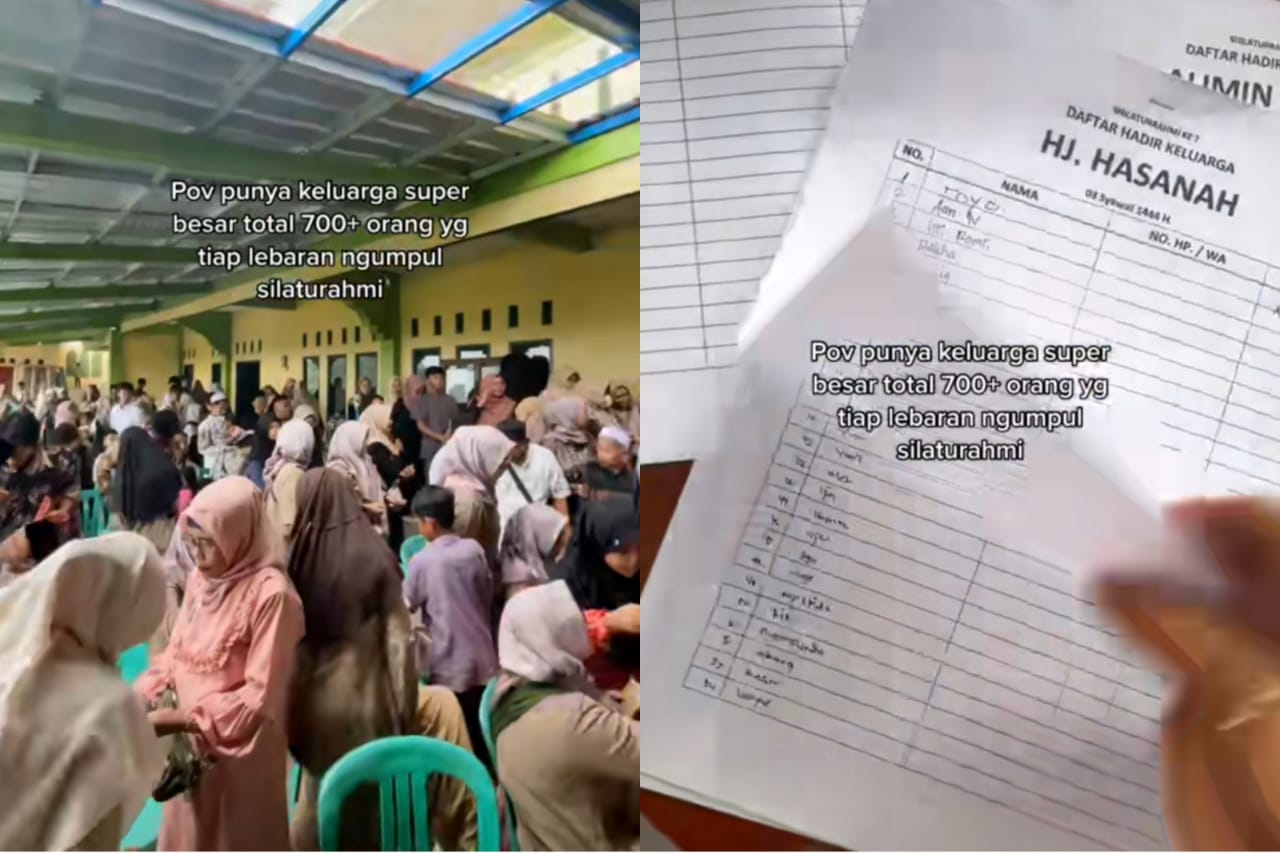Suara Temaram di Gedung Eks Belanda: Lorong Bisikan Masa Lalu
Arya, seorang arsitek konservasi, menatap gedung tua itu. Fasad kolonialnya yang megah kini tergerus lumut dan cat yang mengelupas. Proyek restorasi ini adalah impian, namun aura bangunan itu terasa dingin, seolah menyimpan rahasia kelam di balik jendela-jendela butanya.
Udara lembap dan bau apak menyambutnya saat ia melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, saksi bisu waktu yang tak terjamah. Ruangan-ruangan kosong terasa luas, namun diiringi bisikan samar yang seolah berdesir dari dinding.
Arya mengabaikannya, menganggapnya hanya suara angin yang berinteraksi dengan struktur tua. Ia mengeluarkan sketsa dan alat ukur, mulai pekerjaannya dengan profesionalisme tinggi. Gedung itu, bekas kantor dagang VOC, memiliki sejarah panjang yang menarik.
Namun, di hari kedua, bisikan itu kian jelas. Bukan lagi desiran angin, melainkan seperti gumaman, jauh dan tak terartikulasi. Terkadang, terdengar alunan melodi kuno, lamat-lamat, seperti lagu pengantar tidur yang terputus di tengah.
Ia mendapati dirinya sering berhenti, menajamkan pendengaran. Apakah ia lelah? Atau imajinasinya bermain-main di tengah kesunyian gedung yang mencekam ini? Arya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ilusi akustik.
Malam itu, Arya memutuskan menginap di salah satu ruangan yang lebih bersih, dekat jendela besar. Ia ingin merasakan atmosfer bangunan di luar jam kerja. Sebuah keputusan yang kelak akan disesalinya.
Saat kegelapan melingkup, gedung itu seolah hidup. Suara-suara itu kini lebih berani. Langkah kaki pelan di lantai atas, gesekan kain, bahkan tawa cekikikan yang tipis, melayang di koridor kosong.
Jantung Arya berdebar kencang. Ia menyalakan senter, menyapu cahaya di sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, suara-suara itu tetap ada, seolah mengitarinya, mengunci dirinya dalam sebuah labirin audio.
Ia bangkit, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Senter di tangannya bergetar sedikit. Ia mengikuti sumber suara yang paling jelas: sebuah melodi pilu yang berasal dari ujung koridor lantai dua.
Koridor itu gelap gulita, berujung pada sebuah pintu kayu ek tua yang tertutup rapat. Dari celah di bawah pintu, terlihat cahaya temaram, berkedip-kedip seperti lilin. Aroma melati yang kuat menusuk hidungnya.
Arya mendekat perlahan. Melodi itu semakin keras, kini terdengar seperti tangisan yang dilantunkan. Ia menyentuh gagang pintu, terasa dingin dan berkarat. Sebuah bisikan menusuk telinganya, seolah tepat di sampingnya.
“Jangan masuk…”
Arya terlonjak mundur, nyaris menjatuhkan senternya. Suara itu jelas, sebuah bisikan wanita yang penuh kepedihan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh, namun tak ada siapa pun.
Ketakutan mencekamnya, namun rasa penasaran akan sumber suara dan cahaya itu jauh lebih kuat. Dengan gemetar, ia mendorong pintu. Engselnya berderit panjang, memecah kesunyian malam.
Di dalamnya, sebuah ruangan kecil yang kotor dan berdebu. Hanya ada sebuah meja kayu bobrok, sebuah kursi, dan beberapa perkakas tua. Sumber cahaya temaram itu berasal dari sebuah lampu minyak yang goyah di sudut.
Di atas meja, tergeletak sebuah buku harian lusuh dengan sampul kulit. Arya meraihnya, debu berhamburan. Di halaman pertama, tertulis tanggal 1887 dan nama ‘Elara’. Melodi pilu itu tiba-tiba berhenti.
Hening yang mematikan memenuhi ruangan. Arya membuka buku harian itu, tangannya sedikit gemetar. Tulisan tangan yang anggun namun rapuh memenuhi halaman. Elara adalah seorang pribumi, pelayan di gedung ini.
Ia menulis tentang cintanya yang terlarang dengan seorang pejabat Belanda, Van der Meer. Kisah mereka penuh gairah namun juga keputusasaan, tersembunyi dari pandangan masyarakat kolonial yang kaku.
Elara juga menulis tentang kehamilannya. Ketakutan, harapan, dan janji-janji Van der Meer untuk melarikan diri bersamanya. Namun, bab-bab selanjutnya dipenuhi kegelisahan dan firasat buruk.
Suatu malam, Van der Meer datang dengan wajah pucat. Ia diancam akan dipulangkan ke Belanda jika hubungannya dengan Elara terbongkar. Demi karirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Elara dan anak mereka.
Elara memohon, menangis, namun Van der Meer tak bergeming. Ia memberinya sejumlah uang dan memintanya pergi, melupakan semua yang terjadi. Hati Elara hancur, terbayang nasibnya sebagai seorang ibu tunggal di masa itu.
Paragraf terakhir buku harian itu ditulis dengan tergesa-gesa, tinta mengering tak sempurna. Elara mengungkapkan keputusasaannya, rasa sakit yang tak tertahankan, dan tekadnya untuk tetap tinggal di gedung ini.
Ia ingin anak mereka, yang belum lahir, suatu hari mengetahui kebenaran. Ia akan bersembunyi di suatu tempat, menunggu. Jika ia tak selamat, suaranya akan tetap ada, berbisik di antara dinding-dinding ini.
Arya menutup buku harian itu, hatinya dipenuhi kesedihan. Jadi, “suara temaram” itu adalah Elara. Sebuah arwah yang terperangkap dalam kepiluan, mencari keadilan atau sekadar pengakuan atas kisahnya.
Ia mengamati ruangan itu lagi. Di balik sebuah lemari tua yang teronggok, ia melihat ada celah. Dengan susah payah, ia menggeser lemari itu. Di sana, sebuah pintu tersembunyi yang nyaris tak terlihat.
Di baliknya, sebuah lorong sempit, gelap, dan berbau apek. Arya menyalakan senternya dan melangkah masuk. Lorong itu berliku, menurun ke bawah tanah. Suara-suara Elara kembali, kini lebih jelas.
Bisikan-bisikan itu bukan lagi gumaman, melainkan ratapan, isak tangis, dan alunan lagu pengantar tidur yang pilu. Arya berjalan terus, melewati sarang laba-laba dan kelelawar yang beterbangan.
Lorong itu berakhir di sebuah ruangan bawah tanah yang lebih besar, namun gelap gulita. Di tengah ruangan, sebuah ranjang besi tua yang berkarat. Di atasnya, sebuah kain lapuk menutupi sesuatu.
Arya mendekat, jantungnya berdetak tak keruan. Ia menarik kain itu perlahan. Di bawahnya, terbaring sebuah kerangka kecil, terbungkus kain tipis yang sudah hancur. Sebuah kerangka bayi.
Dan di sampingnya, sebuah boneka kain lusuh, dan sebuah liontin perak berkarat. Liontin itu terbuka, memperlihatkan ukiran inisial “E” dan “V”. Air mata Arya menetes, membasahi debu.
Melodi pilu itu tiba-tiba berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan alunan lembut, seperti bisikan terima kasih. Aroma melati memenuhi ruangan, jauh lebih pekat dari sebelumnya.
Arya merasakan sentuhan dingin di bahunya, sebuah usapan lembut yang segera menghilang. Ia tahu, Elara ada di sana, di sampingnya, akhirnya ditemukan. Kisahnya, anaknya, tidak lagi tersembunyi.
Ia duduk di sana untuk waktu yang lama, membiarkan kesunyian yang damai menyelimutinya. Suara-suara itu kini telah sirna, digantikan oleh ketenangan. Elara telah menemukan kedamaiannya.
Arya memutuskan untuk tidak merenovasi ruangan bawah tanah itu. Ia akan memastikan kisah Elara dan anaknya tercatat dalam sejarah gedung itu, bukan sebagai cerita hantu, melainkan sebuah tragedi manusia.
Gedung itu kini akan memiliki suara baru. Bukan lagi bisikan temaram yang mencekam, melainkan gema dari sebuah kisah cinta terlarang dan pengorbanan, yang akhirnya menemukan jalan menuju cahaya.
Saat matahari terbit, memancarkan sinarnya ke dalam gedung, Arya keluar. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Gedung itu, yang dulunya terasa dingin dan penuh misteri, kini terasa seperti monumen keheningan yang bermartabat.
Suara temaram itu telah pergi, digantikan oleh kenangan. Dan Arya tahu, bahwa setiap bangunan tua menyimpan lebih dari sekadar bata dan mortar; mereka menyimpan cerita, bisikan dari jiwa-jiwa yang pernah menghuni mereka.